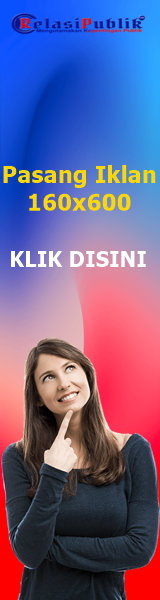LABUHANBATU — Kejadian kekerasan terhadap wartawan, perusakan rumah wartawan, bahkan pembunuhan, bukan lagi cerita jarang di negeri ini.
Kasus-kasus tersebut bukan hanya luka fisik atau trauma pribadi, melainkan juga luka terhadap demokrasi, terhadap hak publik untuk mengetahui kebenaran, terhadap kebebasan pers.
Salah satu nama yang muncul dalam sorotan media adalah AKBP Dr. Bernhard L. Malau yang menjabat Kapolres Labuhanbatu sebelum digantikan oleh AKBP Choky Sentosa Meliala.
Adapun beberapa kasus penting yang patut mendapat perhatian yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu beberapa waktu sebelumnya, yakni:
Pembakaran rumah wartawan
Rumah wartawan Junaidi Marpaung, anggota PWI Sumut, dibakar oleh pelaku yang diduga terkait dengan Ormas dan jaringan narkoba. Pelakunya telah berhasil ditangkap.
Kapolres saat itu, Bernhard L. Malau, melalui Polres Labuhanbatu, menyatakan pengungkapan kasus tersebut, termasuk menangkap pelaku, sebagai bentuk keseriusan aparat.
Pengeroyokan wartawan oleh ketua OKP
Tahun 2022, tujuh orang ditangkap atas kasus pengeroyokan terhadap wartawan di Labuhanbatu. Otaknya adalah ketua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
Dan kasus baru yaitu Debt Collector aniaya Wartawan pada 19 September 2025, dua wartawan media online, Andi Putra dan Ahmad Idris, dilaporkan dikeroyok oleh sekelompok debt collector di depan kantor ACC Finance Rantauprapat. Korban sedang membantu warga dalam persoalan penarikan mobil.
Kapolres Bernhard L. Malau dikenal publik tak hanya karena jabatan, tetapi juga karena berbagai catatan kontroversial selama masa jabatannya, ada dugaan menerima “setoran” dari napi narkoba, ada kejanggalan dalam kasus penetapan atau pelepasan tersangka, dan SP3 kasus yang menurut beberapa kalangan seharusnya tetap diproses.
Namun, di saat bersamaan, di beberapa kasus seperti pembakaran rumah wartawan, aparat di bawah kepemimpinannya, atau Polres Labuhanbatu secara keseluruhan — melakukan aksi tangkap pelaku dan pengungkapan, yang mendapat apresiasi dari PWI Sumut.
Mutasi posisi Kapolres yang kemudian diganti oleh AKBP Choky Sentosa Meliala pada Maret 2025 memunculkan pertanyaan.
Apakah pergantian jabatan ini akan membawa perbaikan dalam menegakkan hukum yang melindungi pers secara lebih kuat?
Menangkap pelaku adalah langkah awal yang sangat penting. Namun hukum harus bicara dengan bahasa yang lebih dalam, yang mengakui bahwa wartawan bukan hanya korban kekerasan — mereka adalah pelaku fungsi publik, penyalur suara rakyat, penjaga transparansi.
Hanya menggunakan pasal pengeroyokan atau penganiayaan seperti dalam KUHP, meskipun sah, sering kali membuat dampak pelanggaran tersebut berhenti di tingkat permukaan.
Pengakuan resmi atas profesi wartawan
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara jelas melindungi wartawan, khususnya dalam pasal yang mengatur bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik” dapat dihukum.
Pengabaian pasal ini menyiratkan bahwa profesi wartawan tidak dihargai sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.
Untuk menerapkan pasal perintangan kerja jurnalistik, harus dibuktikan bahwa wartawan dalam keadaan menjalankan tugas jurnalistik — meliput, merekam, mengambil data, membuat laporan.
Kadang aparat menghindar dari penggunaan UU Pers karena dianggap sulit menetapkan bahwa wartawan “sedang bekerja” dalam konteks yang dihadapi.
Jika pasal pengeroyokan saja yang digunakan, pelaku mungkin dihukum kekerasan fisik, tapi pelanggaran terhadap kebebasan pers sebagai fungsi publik tidak diakui. Efek jera menjadi terbatas.
Komunitas pers, masyarakat, dan media berharap bahwa penggunaan UU Pers akan memberikan preseden bahwa kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran terhadap demokrasi itu sendiri.
Tanggung jawab pejabat kepolisian
Kapolres sebagai pimpinan di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan nada penegakan hukum.
Jika beliau secara aktif mendorong pengunaan pasal UU Pers, publik akan melihat komitmen nyata.
Namun jika hanya menangkap pelaku berdasarkan KUHP dan tidak mengeksplorasi UU Pers, maka ada kemungkinan hukum “berjalan setengah hati”.
Berdasarkan beberapa kasus di Labuhanbatu, berikut beberapa catatan penting:
Gunakan UU Pers dalam setiap kasus kekerasan terhadap wartawan
Kapolres, Kapolda, dan aparat kepolisian di daerah harus menjadikan UU No. 40/1999 sebagai rujukan utama ketika wartawan dalam tugasnya dianiaya, dihalangi liputannya, rumahnya dibakar, atau menghadapi ancaman.
Pelibatan PWI atau organisasi pers lainnya dalam proses investigasi sudah seharusnya, termasuk kejelasan status korban sebagai wartawan dalam setiap tahap. Kejelasan motif pemberitaan harus diperiksa, bukti harus dipublikasikan — agar publik tahu bahwa kasus ini bukan sekadar penganiayaan biasa.
Mutasi jabatan, ganti Kapolres, bukanlah solusi jika struktur dan budaya kerja tidak berubah. Propam, Pengawasan Internal, Pengadilan harus memastikan tidak ada oknum aparat yang membiarkan kasus “dilepaskan” secara tidak wajar, atau SP3 (Surat Pemberhentian Penyidikan) dilakukan tanpa alasan yang memadai.
Perlindungan lebih awal untuk wartawan
Deadlines, liputan konflik, pengaduan terhadap oknum pejabat atau partai politik, semua itu rentan memicu reaksi keras. Pemerintah daerah dan kepolisian harus menyediakan mekanisme perlindungan awal: hotline pengaduan mudah, pengawalan ketika liputan berisiko, serta pelatihan hak dan pelaporan bagi wartawan.
Organisasi pers harus terus mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan agar tak hanya dilaporkan, tapi diperoleh keputusan hukum yang memadai.
Publikasi, advokasi, tekanan sosial sangat penting agar aparat tidak nyaman “berdiam”. Satgas Anti Kekerasan Wartawan seperti yang dibentuk PWI adalah langkah bagus, tetapi tugasnya berat: membawa kasus dari berita ke pengadilan dengan penggunaan pasal yang tepat.
Kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan di Labuhanbatu, mulai dari pembakaran rumah, pengeroyokan, hingga laporan dua wartawan yang dibantu warga — menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan masih setengah hati.
Nama Kapolres Bernhard L. Malau muncul dalam beragam catatan, banyak kritik, tetapi juga beberapa pengungkapan yang diapresiasi. Mutasi jabatannya mungkin memberi harapan baru.
Namun hukum dan aparat tidak boleh tergantung pada satu nama atau satu periode jabatan. Perubahan harus struktural, sistemik, dan konsisten.
Negara yang demokratis tidak cukup hanya menegakkan KUHP. Negara harus menegakkan UU Pers secara nyata ketika kebebasan pers dihadapkan pada kekerasan atau intimidasi.
Hukum harus bicara dengan jiwa jurnalistik, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakui bahwa wartawan adalah garda depan dalam menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan kebenaran publik.
Jika hukum tidak merespon dengan bahasa tersebut, maka kita bukan hanya kehilangan wartawan akan tetapi kita kehilangan demokrasi itu sendiri.
Media ini coba menggali informasi dari berbagi sumber perihal wartawan mengalami tindak kekerasan. Sebenarnya ada dua “ruang hukum” yang bisa dipakai.
Pertama, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ini payung hukum pidana umum, yang biasanya dipakai polisi untuk menjerat pelaku. Misalnya Pasal 170 KUHP: tentang pengeroyokan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
Jikalau wartawan dipukul atau dikeroyok, aparat cenderung masuk lewat jalur pidana umum ini karena dianggap “lebih mudah” pembuktiannya: ada visum luka, ada rekaman video, ada saksi.
Kedua, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di sini ada Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan.
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”
Nah, pasal ini secara khusus dibuat untuk melindungi wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya. Jadi kalau ada orang yang menghalangi, mengintimidasi, atau menganiaya wartawan saat meliput, seharusnya bisa dikenakan pasal ini.
Pertanyaannya kenapa sering tidak dipakai pasal “perintangan kerja jurnalistik?”
Alasan praktis penegak hukum, Pasal di KUHP dianggap lebih gampang diproses di pengadilan, karena kategorinya jelas yakni pengeroyokan/penganiayaan.
Alasan lain, kurangnya pemahaman atau tidak semua aparat memahami UU Pers secara utuh atau punya sensitivitas terhadap perlindungan kerja jurnalistik.
Atau terkadang aparat enggan menggunakan pasal “menghalangi kerja jurnalistik” karena akan membuka ruang lebih luas untuk keterlibatan Dewan Pers, sehingga prosesnya jadi lebih “ribet” dibanding hanya pakai KUHP.
Alasan pembuktian: Untuk menjerat dengan pasal perintangan kerja jurnalistik, harus jelas bahwa tindakan itu langsung menghalangi kegiatan jurnalistik (misalnya liputan, wawancara, pengambilan gambar). Kalau tidak ada bukti kuat bahwa korban sedang menjalankan fungsi jurnalistik, aparat memilih jalur umum (pengeroyokan).
Jadi singkatnya, Polisi lebih sering pakai pasal pengeroyokan/penganiayaan (KUHP) karena mudah dibuktikan.
Sementara pasal perintangan kerja jurnalistik (UU Pers) sebenarnya lebih tepat secara profesi, tapi sering diabaikan karena faktor teknis, pemahaman, dan keberanian aparat.
Laporan: Aiman Ambarita.