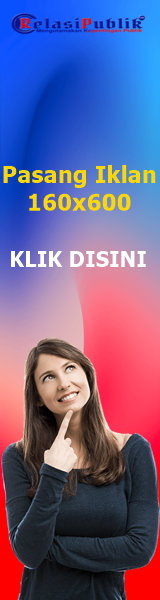LABUHANBATU–Di banyak ruang diskusi tentang pers, kita sering mendengar adagium klasik: “jurnalisme adalah panggilan hati.” Kalimat ini seakan menjadi pengingat bahwa profesi wartawan sejatinya tidak semata pekerjaan mencari nafkah, melainkan amanah untuk menjaga akal sehat publik.
Namun, dalam realitas yang semakin keras dan penuh tuntutan, adagium itu perlahan terdorong ke pinggir. Yang tersisa justru pandangan pragmatis: sukses jurnalis diukur dari seberapa banyak uang yang ia bawa pulang.
Jika orientasi seorang jurnalis sukses hanya diukur dari besarnya pemasukan, maka ilmu pengetahuan yang dengan susah payah mereka gali akan menjadi sia-sia.
Semua pelatihan tentang teknik menulis, semua kuliah tentang etika jurnalistik, bahkan semua jam kerja panjang untuk memahami konstruksi berita—akan terlihat seakan tak berguna. Sebab akhirnya, ukuran keberhasilan bukan lagi mutu tulisan atau kedalaman riset, melainkan seberapa tebal amplop atau seberapa lancar aliran transfer.
Ilmu yang Tergusur oleh Pragmatisme
Generasi wartawan muda sejatinya datang dengan semangat. Mereka lahir dari ruang-ruang kelas yang mengajarkan teori pers, dari seminar-seminar tentang kebebasan informasi, atau dari pengalaman organisasi kampus yang mengasah kepekaan sosial. Mereka datang dengan idealisme bahwa menulis berita adalah jalan untuk memperjuangkan kebenaran.
Sayangnya, di ruang praktik, banyak yang kemudian terjerembab. Mereka mendapati kenyataan pahit: sukses tidak butuh ketekunan menulis berita dengan akurat, tidak memerlukan kecermatan dalam melakukan riset, apalagi kejelian membangun angle.
Yang lebih cepat dihargai adalah kelihaian merangkai kata untuk menakut-nakuti objek liputan, atau kepandaian melobi narasumber dengan gaya basa-basi yang ujungnya bermuatan transaksi.
Di titik inilah pragmatisme menggeser peran ilmu. Apa gunanya belajar piramida terbalik dalam menulis berita jika ujung-ujungnya berita itu tidak pernah tayang karena lebih menguntungkan dijadikan bahan barter? Apa pentingnya etika jurnalistik jika lebih mudah mendapat pemasukan lewat intimidasi terselubung?
Jurnalis Sebagai “Penjaga Gerbang Uang”
Sejarah panjang jurnalisme selalu menempatkan wartawan sebagai watchdog—anjing penjaga kepentingan rakyat. Mereka mengawasi kekuasaan, menelanjangi kebijakan yang korup, serta memberi suara pada kelompok yang terpinggirkan. Tetapi, ketika orientasi berubah, fungsi ini pun bergeser.
Kini, di banyak tempat, jurnalis justru tampil sebagai “penjaga gerbang uang.” Mereka menulis bukan karena kepentingan publik, melainkan karena ada sponsor yang membayar.
Mereka mendekati narasumber bukan untuk menggali informasi yang benar, melainkan untuk membuka peluang transaksi. Berita pun tidak lagi menjadi jendela kebenaran, melainkan papan iklan terselubung atau alat tekan demi keuntungan sesaat.
Bayangkan bagaimana rusaknya ekosistem informasi ketika kondisi ini menjadi kebiasaan. Publik kehilangan kepercayaan pada media. Apa pun yang ditulis dianggap bias, penuh pesanan, dan jauh dari kenyataan.
Pada akhirnya, jurnalisme bukan lagi benteng demokrasi, melainkan sekadar mesin pencetak uang yang rapuh.
Warisan Buruk untuk Generasi Muda
Bahaya lain dari orientasi uang adalah warisan buruk bagi generasi jurnalis muda. Alih-alih diajarkan tentang integritas, mereka justru belajar tentang cara-cara kotor yang dianggap lebih cepat mendatangkan hasil.
Mereka melihat seniornya lebih dihargai karena punya jaringan transaksi, bukan karena mutu liputan. Mereka mendengar bahwa karier wartawan bukan ditentukan oleh prestasi menulis, melainkan oleh seberapa besar ia bisa mengelola “jaringan setoran.”
Padahal, pendidikan formal di kampus, buku-buku teori, dan semua seminar pers selalu menekankan pentingnya etika, keberimbangan, dan akurasi.
Ironinya, semua itu hanya berhenti di ruang kelas. Begitu masuk lapangan, yang terjadi adalah benturan dengan realitas bahwa idealisme tidak cukup untuk membeli bensin atau membayar kos. Dari sinilah lahir dilema klasik: idealis atau realistis?
Jurnalisme Bukan Jalan Cepat Kaya
Kita perlu jujur mengakui: jurnalisme memang bukan profesi untuk cepat kaya. Gaji wartawan di banyak daerah masih sangat rendah, bahkan seringkali tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok. Situasi ini membuka ruang bagi praktik-praktik transaksional yang sulit dihindari.
Namun, menjadikan uang sebagai orientasi utama jelas bukan solusi. Sebab begitu itu terjadi, jurnalisme kehilangan kompas moralnya. Alih-alih memperbaiki keadaan, justru makin terjerat dalam lingkaran setan.
Wartawan yang sudah terbiasa “bermain uang” akan sulit keluar. Sementara publik yang sudah terlanjur sinis terhadap media akan makin enggan percaya.
Di sinilah dibutuhkan kesadaran kolektif: jurnalisme adalah jalan panjang. Ia memang melelahkan, penuh risiko, bahkan sering membuat frustrasi. Tetapi di balik semua itu, ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan uang: ketika sebuah berita mampu membuka mata banyak orang, ketika liputan investigasi mengguncang kekuasaan, atau ketika suara rakyat kecil akhirnya terdengar lewat halaman media.
Orientasi Alternatif: Integritas dan Dampak
Mungkin sudah saatnya kita merevisi ukuran sukses bagi seorang jurnalis. Bukan lagi seberapa besar uang yang dikantongi, melainkan seberapa besar dampak yang dihasilkan.
Apakah tulisannya mampu mendorong perubahan kebijakan? Apakah beritanya membuat publik lebih sadar? Apakah liputannya memberi ruang bagi mereka yang tak punya suara?
Integritas harus kembali dijadikan orientasi. Uang memang penting, tapi ia bukan tujuan—melainkan akibat. Penghargaan finansial akan datang ketika kredibilitas terbentuk.
Media yang menjaga kepercayaan publik akan lebih mudah mendapat dukungan, baik dari pembaca maupun dari mitra yang sehat. Wartawan yang menjaga reputasi akan lebih dihargai dalam jangka panjang.
Mengembalikan Roh Jurnalisme
Tentu, tidak mudah mengubah orientasi ini. Dibutuhkan kerja bersama: perusahaan media yang berani memberi upah layak, organisasi profesi yang konsisten menegakkan kode etik, lembaga pendidikan yang tidak hanya menjejalkan teori tetapi juga membekali mahasiswa dengan realitas lapangan, serta wartawan sendiri yang rela menahan godaan pragmatisme.
Mengembalikan roh jurnalisme berarti mengembalikan jati diri profesi ini sebagai penopang demokrasi. Tanpa itu, wartawan hanya akan menjadi pedagang kata, dan media hanya menjadi pasar transaksi.
Pada akhirnya, ukuran sukses seorang jurnalis tidak bisa semata-mata ditakar dengan uang. Ia harus ditimbang dari mutu karya, dampak sosial, dan integritas pribadi. Jika generasi wartawan muda hanya diajarkan mengejar materi, kita sedang menyiapkan jurnalisme yang kehilangan arah.
Sebaliknya, jika mereka diarahkan untuk menjadikan ilmu menulis, etika, dan keberanian sebagai pegangan, maka uang bukanlah tujuan, melainkan penghargaan yang datang dengan sendirinya. Uang bisa habis, tetapi integritas akan selalu dikenang. Dan hanya dengan itulah jurnalisme tetap bisa berdiri tegak sebagai cahaya dalam gelap, bukan sebagai bayangan kelam yang menakutkan.
Editor: Aiman Ambarita