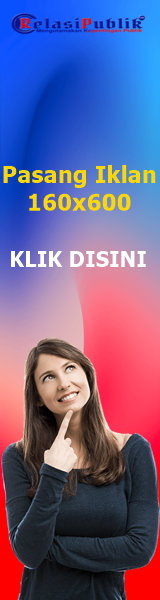Ket Foto: Korban HS mendatangi Propam Polda Sumut, (25/7/2024).
LABUSEL — Di atas kertas, hukum Indonesia sudah sangat jelas: siapa pun yang menjadi korban tindak pidana berhak melapor ke polisi, dan polisi wajib menerima laporan tersebut tanpa menunda atau menyeleksi.
Pasal 108 KUHAP bahkan menegaskan, laporan dapat diajukan oleh siapa saja yang mengalami atau mengetahui tindak pidana. Namun dalam praktik di lapangan, keadilan seringkali terhambat bukan karena rumitnya pasal, melainkan karena salah kaprah administratif.
Kasus yang dialami HS (31) warga Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menjadi contoh nyata. Ia datang ke kantor polisi sebagai korban pemerkosaan, tapi yang keluar dari tangan petugas bukanlah Laporan Polisi (LP), melainkan pengaduan masyarakat (Dumas).
Satu lembar kertas dengan kop Polri, yang sekilas tampak resmi, tapi secara hukum belum memberi jaminan perlindungan dan proses penyidikan.
Dalam struktur birokrasi kepolisian, Dumas (Pengaduan Masyarakat) adalah kanal untuk menampung keluhan, kritik, atau aduan umum terhadap pelayanan publik maupun dugaan pelanggaran.
Dumas bukan laporan pidana, dan tidak otomatis memicu proses penyelidikan. Ia hanya “catatan awal” yang bisa ditindaklanjuti — atau tidak — tergantung penilaian aparat.
Masalahnya, ketika peristiwa pemerkosaan diperlakukan seperti keluhan layanan publik, makna keadilan jadi tereduksi. Korban yang datang mencari perlindungan justru dihadapkan pada ruang abu-abu administrasi: tidak ditolak, tapi juga tidak diterima sebagai perkara hukum.
Padahal, tindak pidana pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) adalah delik biasa, artinya polisi wajib memproses meski tanpa aduan resmi dari korban.
Mengkategorikannya sebagai Dumas berarti menunda akses korban terhadap keadilan, termasuk hak untuk visum, perlindungan LPSK, dan proses penyidikan.
Beberapa aparat berdalih, pencatatan Dumas dilakukan karena laporan belum dilengkapi bukti atau saksi. Padahal, hukum acara pidana tidak menuntut bukti lengkap di awal pelaporan. Laporan dibuat justru agar penyidik bisa mencari dan mengumpulkan bukti.
Praktik seperti ini sudah menjadi kebiasaan di banyak kantor polisi daerah. Ia seolah menjadi “filter” agar tidak semua aduan langsung naik ke penyidikan. Tapi untuk kasus kekerasan seksual, “menunda” berarti memperpanjang penderitaan korban.
Korban seperti Herlina membutuhkan kepastian, bukan prosedur yang berbelit. Ia datang dengan keberanian besar — mengungkap trauma yang mestinya cukup jadi mimpi buruk, bukan berkas administrasi.
Dampak Fatal bagi Korban dan Sistem Hukum
Kesalahan administratif seperti ini bukan persoalan sepele. Ia bisa menimbulkan dampak fatal baik bagi korban maupun sistem hukum secara keseluruhan.
Pertama, dampak psikologis. Korban pemerkosaan datang dengan luka batin yang belum sembuh. Saat laporannya hanya diterima sebagai Dumas, ia merasa tidak dipercaya, bahkan diremehkan oleh negara.
Kondisi ini dapat memperparah trauma, menyebabkan depresi, rasa bersalah, dan hilangnya kepercayaan pada aparat penegak hukum.
Kedua, dampak hukum. Karena tidak tercatat sebagai laporan polisi (LP), maka tidak ada proses penyidikan resmi. Artinya, pelaku bebas berkeliaran, barang bukti bisa hilang, dan visum mungkin tidak segera dilakukan.
Keterlambatan ini bisa mengaburkan jejak kejahatan, membuat pembuktian menjadi sangat sulit — bahkan mustahil di kemudian hari.
Ketiga, dampak sosial. Dalam masyarakat kecil seperti Torgamba, kabar cepat menyebar. Korban bisa mengalami stigma, fitnah, atau pengucilan.
Ketika kasusnya tidak segera diproses, masyarakat bisa berasumsi bahwa korban berbohong atau mencari perhatian. Sementara pelaku tetap menjalani kehidupan normal, seolah tak bersalah. Di titik ini, masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap hukum.
Lebih jauh lagi, kesalahan prosedur seperti ini juga merusak integritas institusi penegak hukum. Ia menanamkan pesan buruk: bahwa keadilan hanya berlaku bagi mereka yang punya keberuntungan administratif, bukan bagi yang benar-benar menderita.
Perlakuan semacam ini mengubah wajah hukum dari pelindung menjadi pagar birokrasi.
Bayangkan, seorang perempuan yang baru saja mengalami kekerasan seksual harus menjelaskan kronologi pahit, hanya untuk diberi kertas bertuliskan “Dumas”. Tidak ada nomor laporan, tidak ada penyidik yang ditugaskan, dan tidak ada tindak lanjut yang pasti.
Dalam konteks ini, Dumas justru menjadi penghalang psikologis dan pengabaian hukum. Padahal, negara telah berkomitmen lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan disangsikan.
Penundaan status laporan bukan hanya soal administratif — ia bisa menjadi bentuk maladministrasi pelayanan publik.
Ombudsman RI, Kompolnas, dan Propam Polri memiliki kewenangan menindak aparat yang mengabaikan kewajiban menerima laporan pidana. Namun mekanisme ini sering baru berjalan setelah korban bersuara ke publik.
Itulah sebabnya, pengawasan publik dan tekanan moral media menjadi penting. Karena dalam banyak kasus kekerasan seksual, keberanian korban tidak cukup tanpa keberanian lembaga untuk menegakkan hukum.
Kasus HS boru Sitorus semestinya menjadi alarm bagi institusi penegak hukum. Dumas bukanlah tempat bagi penderitaan seorang korban kekerasan seksual. Polisi tidak boleh bersembunyi di balik alasan “verifikasi” atau “proses administratif”, karena setiap penundaan berarti memperpanjang luka.
Jika aparat masih menunda status laporan korban, maka sesungguhnya yang diperkosa bukan hanya tubuh perempuan itu — tapi juga rasa keadilan kita sebagai bangsa.
Laporan: Aiman Ambarita